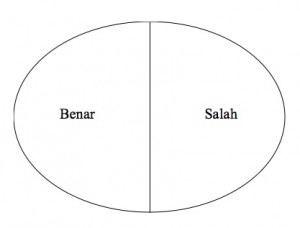![]()
Gambar diambil dari https://lh5.googleusercontent.com
KETIKA Suharto turun dari tampuk kekuasaan, medan seni lukis di Indonesia sama sekali lain bila dibandingkan dengan sewaktu ia merebut kekuasaan dari tangan Sukarno.[1] Ketika ia meraih kekuasaan, estetika Modernis sedang gencar-gencarnya dimajukan oleh para pelukis Indonesia, lukisan abstrak menjamur di mana-mana dan seni lukis menjadi ujung tombak seni rupa. Ketika ia mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan, estetika pascamodern sedang ramai-ramainya diwacanakan, beragam praktik kesenirupaan sudah berkembang jauh melampaui bidang dua-dimensi dan seni lukis bukan lagi paradigma utama seni rupa. Apa yang terjadi dengan medan seni lukis kita selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru? Apa yang menjelaskan pergeseran dari modernisme ke pascamodernisme dalam estetika seni rupa kita? Apa sebetulnya akar dari estetika seni lukis yang berkembang pada masa Orde Baru? Namun sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan besar itu, kita akan periksa terlebih dulu suatu pertanyaan awal yang bisa memantik diskusi kita: bentuk estetika seni lukis macam apakah yang selaras dengan kepentingan politik kebudayaan Orde Baru?
Mentari Pirous, Lukisan Abstrak dan Politik Kebudayaan Orde Baru
Bambang Bujono pernah menulis bahwa pembubaran Lekra merupakan peristiwa seni rupa Indonesia terpenting sejak dibentuknya Persagi (Bujono 2004: 67). Dengan tumbangnya Lekra, berakhir pulalah suatu tradisi estetika seni lukis yang punya wawasan dan sikap sosial-politik yang eksplisit. Naiknya Orde Baru berarti juga menyeruaknya keperluan akan suatu rezim estetika yang memuja segala yang serba-samar dan ambigu dalam perkara politik. Keperluan inilah yang dengan leluasa diisi oleh seni lukis abstrak. Tentu saja, tradisi seni lukis abstrak, atau setidaknya abstraksionis, di Indonesia tidak dimulai pada masa Orde Baru. Lukisan semacam itu sudah bisa kita temukan jejaknya sejak transformasi dari lukisan-lukisan kubistis ke abstraksionis yang bercorak geometris pada dekade 1950-an dalam karya para pelukis seperti But Muchtar, Mochtar Apin dan Srihadi Sudarsono. Namun dalam lukisan abstraksionis, masih bisa kita temukan sosok, ilusi representasi dan karenanya subject matter. Tidak demikian halnya dengan lukisan abstrak, seperti misalnya “Komposisi Abu-Abu” (1966) karya G. Sidharta atau “Komposisi Dengan Emas” (1967) karya Sadali. Permulaan masa Orde Baru ditandai dengan merebaknya lukisan abstrak semacam itu.
Bersamaan dengan tumbuh-kembangnya gaya lukis abstrak di Indonesia pada dekade 1960-an dan 1970-an berkembanglah suatu tradisi estetik yang disebut Sanento Yuliman sebagai lirisisme. Dalam lukisan-lukisan abstrak terkandung corak lirik sejauh setiap lukisan semacam itu, tulis Sanento, “merupakan bidang ekspresif, tempat seorang pelukis seakan-akan ‘memproyeksikan’ emosi dan getaran perasaannya, merekam kehidupan jiwanya. Bidang lukisan itu dipandang sebagai dunia imajinasi yang memiliki kodrat sendiri” (Yuliman 1976: 40). Dalam hal ini, kita perlu membedakan antara lirisisme yang dikandung dalam lukisan abstrak seperti diidentifikasi Sanento dengan ekspresionisme yang muncul dalam generasi awal pelukis Indonesia modern seperti Sudjojono dan Hendra Gunawan. Landasan pemikiran dari gaya ekspresionis, seperti diungkap Sudjojono, adalah bahwa lukisan merupakan ungkapan jiwa—suatu ‘jiwa yang kelihatan’ (jiwa ketok). Walau begitu, ‘jiwa’ ini baru akan kelihatan setelah dihadapkan dengan kenyataan. ‘Jiwa’ dalam pengertian perupa ekspresionis itu berarti kacamata untuk membaca kenyataan. Itulah sebabnya Sudjojono masih bisa berbicara soal kebenaran dalam seni lukis.[2] Lain halnya dengan para pelukis abstrak era 1960/1970-an. Dalam tradisi lirik, apa yang penting bukanlah kebenaran intuisi akan kenyataan, melainkan kekayaan semesta imajinasi yang cukup-diri.
Maka itu, tak aneh bila Sudjojono menentang keras gaya lukis abstrak. Dalam salah satu tulisannya di majalah terbitan ISI pada tahun 1985, Sudjojono menyebut para pelukis abstrak itu “munafik”, “sok suci” dan “makin tidak dimengerti, makin bangga”.[3] Pasalnya, lirisisme abstrak itu seperti hendak menghapuskan tautan antara seni dan kenyataan, membuat lukisan menjadi bidang dua-dimensi yang sepenuhnya swa-acu dan cukup-diri tanpa punya kaitan dengan kenyataan di luarnya. Lukisan abstrak dipandangnya seperti pelarian-diri ke alam privat sembari mengabaikan konteks yang membidani lahirnya seni lukis Indonesia modern, yakni pengalaman penjajahan dan perjuangan melawan penjajahan. Konteks inilah yang mencirikan dengan sangat kuat seni lukis ekspresionis generasi Sudjojono dan membedakannya dari kecenderungan individualis dalam seni lukis abstrak di awal Orde Baru. Di sini kerangka estetik dari seni lukis abstrak lah yang sejatinya dipertanyakan Sudjojono—kerangka estetika seni Modernis.
Modernisme seni adalah sebuah paham estetik yang muncul sejak akhir abad ke-19 lalu mendapatkan ungkapan paripurnanya dalam tulisan-tulisan archmodernist Clement Greenberg di era 1950/1960-an. Pada tahun 1914, Clive Bell telah memberikan landasan teoretis bagi Modernisme seni dalam rupa estetika formalis. Baginya, titik berangkat dari segenap kenyataan artistik adalah perasaan dan emosi. Lukisan mengandung dalam dirinya sendiri bentuk-bentuk bermakna (significant forms), yakni seluruh elemen formal dalam karya yang menimbulkan sensasi emosional, terlepas dari muatan naratif atau acuan representasional yang mungkin dibawanya (Bell 1914: 8). Karya seni yang baik, dalam kerangka estetika formalis ini, adalah karya seni yang murni mengandalkan bentuk bermaknanya ketimbang berhutang pada asosiasi linguistik atau citrawi untuk membangkitkan perasaan keindahan. Itulah sebabnya ia menganggap ‘lukisan deskriptif’ (segala bentuk lukisan representasional) sebagai karya seni yang buruk karena segala aspek formal yang terkandung di dalamnya “tidak digunakan sebagai objek emosi, melainkan sebagai sarana mendorong emosi atau mengantarkan informasi” (Bell 1914: 16).
Kerangka estetika formalis inilah yang membidani lahirnya Modernisme dalam seni rupa. Perupa akhir abad ke-19, James Whistler, adalah salah seorang pelopor gerakan seni tersebut. Karyanya, Nocturne in Black and Gold (1874), atau karyanya yang lebih terkenal, Arrangement in Grey and Black No. 1 (1871), merupakan pembuktian kerangka estetika formalis dalam praktik. Segala acuan representasional dalam karya tersebut, jika pun masih ada, sepenuhnya dikebawahkan pada pertimbangan formal-komposisional. Melalui kerangka estetika macam inilah Greenberg membangun teorinya tentang ‘lukisan Modernis’. Greenberg menegaskan kembali pengertian ‘modern’ dengan acuan pada Kant dan tradisi filsafat modern, yakni kemawasan akan metode. Seni lukis Modernis, karenanya, dibangun di atas kesadaran akan pentingnya menyadari kekhasan metode lukis itu sendiri—pemaparan visual dalam batas-batas bidang dua-dimensi.[4] Bidang kanvas yang dua-dimensional merupakan syarat kemungkinan sekaligus batas-batas seni lukis. Karena itu, tidak seharusnya pelukis menciptakan ilusi kedalaman—melalui teknik lukis perspektif—sebab ini berarti mengkhianati wahana dua-dimensional itu sendiri. Inilah yang dimaksudnya sebagai ‘kekhasan wahana’ (medium specificity) (Greenberg 1999b: 558). Pengkhianatan atas kekhasan wahana akan menurunkan derajat karya seni menjadi kitsch atau produk desain yang bercorak populer dan diproduksi massal tanpa nilai estetis yang mendalam. Oleh sebab itu, apa yang boleh diandalkan para pelukis Modernis hanyalah seluruh aspek formal dari karya. Dalam Modernisme seni, singkatnya, kita menemukan kedaulatan sintaksis atas semantik yang dibangun melalui peminggiran sistematis atas segala yang dianggap kitsch sebagai ‘bukan seni’.
Kecenderungan estetika formalis ini dapat dilihat juga dari cara publik seni merespon karya seni, misalnya dalam tinjauan-tinjauan pameran lukisan yang dibuat di awal Orde Baru. Popo Iskandar, misalnya, menulis dalam harian milik ABRI, Berita Yudha, tentang pameran Sadali bulan Desember 1972: “Hilangnya unsur-unsur penuturan pada seninya Sadali, maka karya-karyanya adalah pertemuan antara renungan-renungan kontemplatif si seniman dan materi yang minta dibentuk di atas kanvas, jadinya ia merupakan sensasi untuk mata yang menggugahkan rasa keindahan badani. Lukisan-lukisan Sadali adalah cantik, dekoratif menyenangkan, yang dengan sendirinya membutuhkan proses pengerjaan yang meminta konsentrasi, kesabaran dan kecermatan” (Iskandar 2012: 203). Kesadaran estetika formalis dalam menjauhi kitsch juga nampak dalam pandangan Fadjar Sidik. Ketika karya-karya abstraknya dianggap ‘lari dari kenyataan’ oleh para perupa Lekra, Fadjar Sidik membalas dengan mempertanyakan secara retoris mengapa para perupa Lekra itu tak menggambar sepeda motor, mesin cuci atau kulkas saja sekalian—toh itu ‘kenyataan’ yang ada sekarang. Fadjar Sidik kemudian menjawab sendiri pertanyaan retorisnya dengan menyatakan kalau mereka melukis hal-hal itu, hasilnya tentu bukanlah karya seni, melainkan reklame semata (Bujono 2004: 72). Pengandaian estetika semacam ini kentara sekali bedanya dengan estetika Lekra seperti tercermin dalam laporan Misbach Tamrin atas pameran seni grafis Lekra di Harian Rakyat tanggal 23 Agustus 1964—laporan yang memberikan perhatian pada aspek sosial-politik dari praktik seni grafis sejajar dengan perhatian pada aspek formal-komposisionalnya, serta tidak mengecilkan arti wahana seni yang bisa diproduksi massal sebagai kitsch yang rendahan.[5]
Kemenangan Orde Baru atas Orde Lama berarti juga kemenangan estetika formalis di atas paham-paham estetik lain yang tumbuh-kembang di era Sukarno (realisme, didaktisisme, fungsionalisme/instrumentalisme). Estetika formalis yang tercermin dalam lukisan-lukisan abstrak dengan cepat dipandang selaras dengan proyek politik kebudayaan Orde Baru. Dalam bukunya bertajuk Strategi Kebudayaan (1978), Ali Moertopo menulis bahwa “Orde Baru adalah sebuah proses kebudayaan” (Jones 2005: 136). Konsolidasi kapitalisme-negara pada zaman Orde Baru mensyaratkan konsolidasi kebudayaan nasional. Dalam konteks kesenian, Orde Baru membutuhkan jenis praktik kesenian yang tidak kritis pada pemerintah, yang tak mencampuri urusan politik—singkatnya, yang sibuk sendiri. Estetika formalis dengan pas menjawab kebutuhan ini. Dengan membuat seniman sibuk pada ‘kekhasan wahana’-nya sendiri, formalisme memberikan legitimasi bagi pengasingan dunia seni dari semesta politik. Sementara sanggar-sanggar seni komunis dan nasionalis dibubarkan, para senimannya dibekuk dan dikebumikan-paksa, para seniman di luar kubu itu diarahkan untuk asyik sendiri dengan mistik keindahan formal. Dari sini, dengan cepat lukisan abstrak menjadi identik dengan ‘lukisan pembangunan’, yakni jenis lukisan yang begitu selarasnya dengan semangat pembangunan Orde Baru sampai-sampai segera memenuhi rumah-rumah kelas menengah atas serta kantor-kantor pemerintah dan perusahaan swasta (Siregar 2010: 105-106).
Keterkaitan erat antara pengarus-utamaan gaya lukis abstrak dengan estetika formalisnya dan politik kebudayaan kapitalisme bukanlah fenomena khas Indonesia saja. Di Amerika Serikat, gaya lukis dan estetika semacam itu telah lama disinyalir punya hubungan kerabat dengan CIA. Dalam jurnal Artforum tahun 1974, Eva Cockcroft menulis artikel klasik bertajuk Abstract Expressionism, Weapon of the Cold War. Di sana Cockcroft menunjukkan intervensi CIA antara lain melalui lembaga seni berpengaruh, Museum of Modern Art (MoMA). Jabatan ketua dewan pembinanya pernah diisi oleh John Hay Whitney, seorang mantan pejabat OSS (lembaga pendahulu CIA). Lewat lembaga inilah serangkaian pameran lukisan abstrak-ekspresionis digelar di Eropa di akhir dekade 1950-an yang karya-karyanya, dalam ungkapan sejarawan seni Alfred H. Barr, Jr. dalam katalog pameran tersebut, merupakan “demonstrasi simbolik atas kebebasan dalam dunia di mana kata ‘kebebasan’ berasosiasi dengan sikap politik tertentu” (Cockcroft 1985: 131).[6] Lewat lembaga inilah perupa abstrak-ekspresionis Jackson Pollock memperoleh nama besarnya dan digadang-gadang sebagai seniman terbesar Amerika Serikat pada dekade 1950-an. “Dengan memberikan penekanan individualis dan menghapuskan pokok ihwal yang kentara dari lukisan mereka,” tulis Cockcroft (1985: 132), “para perupa abstrak-ekspresionis berhasil menciptakan gerakan seni baru yang penting. Mereka juga punya sumbangan, entah mereka sadari atau tidak, bagi suatu fenomena politik, yakni perceraian antara seni dan politik yang dengan sempurna melayani kepentingan Amerika Serikat dalam Perang Dingin.”
Dengan begitu, terlihat bagaimana laju kapitalisme dibuat demikian rupa sehingga bergerak sebaris dengan seni lukis abstrak. Dalam konteks Indonesia, keseayunan gerak itu terjadi antara kapitalisme-negara yang dikonsolidasikan Orde Baru dan hegemoni gaya lukis abstrak. Yang tertusuk pada Suharto, berdarah pada para pelukis Modernis Indonesia. Karena itulah mereka dengan riang merespon kejatuhan PKI dan Sukarno. Lukisan Mentari Setelah September 1965 (1968) karya A.D. Pirous adalah salah satu contohnya.
![pirous]()
Mentari Setelah September 1965
cat minyak di atas kanvas, 135 x 150 cm, 1968
(direproduksi dari George 2005: 165)
Karya ini pertama kali dipamerkan dalam sebuah pameran bersama Pirous dan Gregorius Sidharta bertajuk “Dharta-Pirous: Pameran Patung dan Lukisan Dua dari Sebelas Seniman Bandung” pada tahun 1968 di Balai Budaya, Jakarta. Lukisan ini terhitung langka sebab Pirous sendiri nyaris tak pernah mengangkat topik politik sebagai pokok ihwal karya-karyanya. Lukisan ini adalah satu dari dua lukisan Pirous yang mengangkat persoalan politik (yang satunya adalah lukisan ekspresionis Menggapai Kebebasan yang diselesaikan tahun 1966).
Astri Wright, seorang profesor sejarah seni Asia Tenggara di Cornell University, menafsirkan karya tersebut sebagai ekspresi perlawanan atas Orde Baru. Bentuk-bentuk dalam lukisan tersebut ia tafsirkan sebagai sosok laki-laki dan perempuan yang menunduk lesu ke arah tanah, sembari membelakangi matahari yang bersinar terik (George 2005: 25). Namun tafsiran semacam ini telah dibuktikan kekeliruannya oleh antropolog Kenneth George berdasarkan wawancara dengan Pirous pada tahun 1994. Tak dapat dilupakan adalah fakta bahwa Pirous termasuk penanda-tangan Manifes Kebudayaan. Ia jengah dengan iklim kesenian tahun-tahun 1960-an yang diwarnai dengan kritik para seniman Lekra terhadap gaya lukis abstrak sebagai “gaya neokolonial dan imperialis”. Kendati para anggota Lekra memang banyak bicara soal ‘realisme sosialis’, tetapi faktanya Lekra tidak pernah mengharuskan pengadopsian gaya realisme sosialis sebagai satu-satunya gaya berkesenian yang sah. Trubus dan Gambiranom, misalnya, adalah dua pelukis Lekra yang karyanya lebih banyak berupa lukisan potret ketimbang penggambaran adegan-adegan kerakyatan (Bujono 2004: 73). Apa yang ditekankan Lekra hanyalah agar para seniman memiliki simpati pada perjuangan rakyat. Inilah yang tak bisa diterima Pirous. Ketika ditanya tentang keengganannya terlibat dalam partai politik, ia menyatakan: “Tidak, saya ingin menjadi seorang pelukis, titik. Saya tidak ingin terlibat dalam politik. […] Saya tidak ingin melukis tema-tema tersebut” (George 2005: 34). Tak heran, ketika Sukarno jatuh, PKI dan Lekra diuber sampai ke liang kubur, dan Suharto naik ke tampuk kekuasaan, ada kelegaan yang merebak dalam diri Pirous.
Dalam konteks inilah lukisan Mentari Setelah September 1965 diciptakan. Pirous menceritakan dalam wawancaranya dengan George arti penting lukisan tersebut ketika dipamerkan pada tahun 1968. Ia katakan bahwa lukisan tersebut adalah “primadona”, “titik pusat dari seluruh lukisan-lukisan saya”, “fokus saya” dan “[sebuah ekspresi dari] rasa terima kasih tentang situasi saat itu” (George 2005: 39). Ia kisahkan juga pada George bahwa seumur hidup ia tak akan mau menjual karya itu. Pasalnya, Mentari Setelah September 1965 merupakan, tutur Pirous, “sebuah peringatan tentang yang ini, matahari ini yang membawa kebahagiaan setelah ’65 … Adalah hal yang spiritual, yang bisa Anda sebut, sekadar catatan spiritual saya, rekaman spiritual saya” (George 2005: 40-41). Dengan demikian, karya tersebut tak bisa ditafsirkan sebagai simbol pesimisme atau kejengahan terhadap Orde Baru, melainkan justru ekspresi rasa syukur pada Suharto. Dalam wawancaranya, Pirous bahkan merasa sangat terganggu dengan tafsiran yang menyatakan karya tersebut sebagai ungkapan ketidaksukaan pada Orde Baru.[7] Simpatinya pada Orde Baru tidak ambigu. Ketika ditanya pada tahun 1994 apakah seni lukis Indonesia suatu saat nanti dimungkinkan untuk mengungkapkan penderitaan mereka yang terbantai dalam pembasmian komunis, ia menyatakan:
“Mungkin akan lama sebelum hal ini terjadi. Bila suatu saat pemerintahan Soeharto mencapai puncaknya dan kemudian jatuh, atau bila ada orang-orang yang ingin menodai sejarah Indonesia dengan kebohongan, atau dengan sesuatu yang tidak merefleksikan kepentingan mayoritas, [kemudian mungkin] lukisan-lukisan tentang mereka yang terbunuh akan menjadikan mereka pahlawan kembali. Bukankah sejarah selalu seperti itu? Namun untuk sekarang, hal itu belum akan terjadi.” (George 2005: 49; garis bawah dari penulis)
Dalam hal ini, bisa kita lihat, persepsi Pirous atas pembasmian komunis sebetulnya tak jauh beda dari persepsi mereka yang diwawancarai dalam film The Act of Killing. Di situ bisa juga kita lihat bagaimana lukisan abstrak bukannya steril dari politik. Dalam sosok Pirous, komitmen politik itu bahkan terlihat dengan terang benderang.
Pembaca yang kritis bisa saja lantas menyimpulkan bahwa dalam sikap diamnya atas pembantaian ’65, seni lukis abstrak pada awal Orde Baru punya pengandaian estetik yang membedakannya dari seni lukis abstrak di Barat. Di Amerika Serikat, seperti telah kita lihat, seni lukis abstrak difungsikan untuk mensterilkan seni dari politik. Di Indonesia pasca-pembantaian ’65, seni lukis abstrak mendapatkan fungsi lain, yakni untuk mengubur setiap pewacanaan estetik tentangnya (menutup kemungkinan bagi pengambilan tema pembantaian ’65 sebagai subject matter karya seni) dengan jalan menghasilkan ragam karya yang mempersulit, kalau bukan malah memustahilkan, setiap perbincangan politik—karya-karya abstrak non-figuratif. Jika sebelum ’65 estetika formalis berfungsi untuk menandingi Lekra, setelah ’65 estetika tersebut berfungsi untuk mengubur pembicaraan tentang pembantaian ’65. Demikianlah seni lukis Modernis di Indonesia tumbuh dan berkembang di sekitar kuburan massal.
Suasana Batin dan Seni Lukis Awal Orde Baru
Namun Modernisme bukanlah satu-satunya pengandaian estetik yang berlaku dalam riwayat seni lukis modern di permulaan masa Orde Baru. Di balik itu, ada juga percampuran dengan suatu tendensi estetik yang dalam terminologi sejarah estetika Eropa akan disebut sebagai ekspresivisme (bedakan dengan ‘ekspresionisme’ yang merupakan aliran dalam seni lukis). Ketika Oesman Effendi mendefinisikan ‘seni lukis modern’ dalam makalahnya di tahun 1969 yang kontroversial dan memicu debat soal keberadaan ‘seni lukis Indonesia’, ia mengartikannya dalam kerangka yang akan dikenali di Eropa sebagai ekspresivis. Ia mendefinisikannya seperti ini:
“seni lukis sebagai hasil ekspresi dari seorang individu yang penuh cita ingin menyampaikan impuls hatinya, hasrat pernyataan atau manifestasi keakuan sebagai kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, tanpa campur tangan dari kehendak di luar dirinya.” (Effendi 2007: 9)
Dalam definisi seni lukis modern semacam ini, sama sekali tak dapat kita kenali jejak estetika formalis. Apa yang kita temukan adalah visi estetik yang jamak ditemukan di akhir abad ke-19 dalam sebuah periode kultural yang biasanya disebut pasca-Romantik (atau kadang juga ‘Romantik akhir’ atau Late Romantic). Estetikawan seperti Nietzsche dan, di awal abad ke-20, Benedetto Croce serta R.G. Collingwood dikenal sebagai teoretisi ekspresivisme. Dalam kerangka estetika ini, karya seni merupakan ungkapan atau ekspresi dari kehidupan batin sang seniman. Collingwood pernah menulis: “Sebuah karya seni dalam pengertian yang sesungguhnya bukanlah suatu artifak, bukan benda fisik dan teramati yang dihasilkan oleh sang seniman, melainkan sesuatu yang ada semata di kepala sang seniman, hasil imajinasinya sendiri” (Collingwood 1938: 305).
Dalam khazanah seni lukis di Indonesia, pengertian yang diberikan Oesman Effendi tadi punya akarnya pada ungkapan legendaris Sudjojono, juru bicara Persagi. Formulanya sudah sering dikutip: “Kalau seorang seniman membuat suatu barang kesenian, maka sebenarnya buah kesenian tadi tidak lain dari jiwanya sendiri yang kelihatan. Kesenian ialah jiwa-kétok. Jadi kesenian ialah jiwa” (Sudjojono 1946: 69). Namun rumusan Oesman bukan cuma remah-remah dari penyataan Sudjojono; Oesman membelokkan pengertian Sudjojono. Apabila Sudjojono mengakarkan ‘kredo ekspresivis’-nya dalam pandangan-dunia anti-kolonial dan karenanya menyimpan dorongan politik (sehingga ia bisa bicara soal ‘kebenaran’ dalam seni lukis), Oesman mengisolasi ‘kredo ekspresivis’ tersebut. Oesman mengesampingkan dimensi politik pernyataan Sudjojono itu dan lebih menekankan dimensi individualnya. Apabila dalam Sudjojono perangnya adalah antara pelukis-sekaligus-aktivis bangsa jajahan melawan kolonialisme dan menggempur benteng kebudayaannya, dalam Oesman perangnya dipersempit menjadi antara aku-seniman versus masyarakat. Dalam makalah yang sama, ia mengkritik tendensi politis dalam dunia seni lukis menjelang era Orde Baru. Ia katakan:
“Seni lukis Indonesia mulai salah arah. Kalau selama ini—lepas dari nilainya—ia bertolak dari impuls hati, dari gerak dalam jiwa rasa, belakangan, faktor-faktor dari luar banyak ikut menentukan arahnya. […] Percobaan hidup yang pertama dari seni lukis … adalah bagaimana ia menyelesaikan diri dalam konstelasi kehidupan seni yang mulai diwarnai oleh politik […]. Karena ia mesti membawakan motif tertentu dan mesti diselesaikan dalam corak tertentu pula, sadar tak sadar si pelukis berkhianat kepada hasrat impuls diri yang ingin menyatakan keakuannya sebagai produk dari tuntutan zamannya.” (Effendi 2007: 11-14)
Sudjojono tidak berbicara tentang ‘keakuan’ sebagai ‘keakuan’. Dalam salah satu tulisan klasiknya, ia memperlihatkan keterkaitan yang erat antara ‘jiwa’ dan ‘nationaliteit’, atau secara lebih umum lagi aspek kedirian seniman dan cakrawala sosial-politiknya.[8] Ia tidak memisah-misahkan seni dari politik; ia tak mengenal distingsi antara ‘sikap estetik’ dan ‘sikap politik’. Oesman, sebaliknya, sangat menekankan pemisahan itu. Dalam posisi Oesman lah kita temukan ekspresivisme yang lebih menyerupai pandangan estetikawan Eropa pasca-Romantik di muka, yakni suatu ekspresivisme yang tertanam dalam pandangan-dunia individualis.
Ekspresivisme individualis Oesman, sebagaimana ekspresivisme Collingwood, dapat ditarik akarnya pada alam pikir Romantik tentang seniman sebagai sesosok jenius sublim yang tak bisa dimengerti masyarakatnya. Dengan demikian, ekspresivisme semacam itu bertopang pada prakonsepsi tentang sosok seniman sebagai entitas yang secara fundamental berbeda dari ‘orang awam’ atau ‘masyarakat biasa’. Ini adalah gejala yang telah muncul sejak lama dalam sejarah seni lukis di Indonesia. Dalam artikelnya di majalah Budaya Jaya tahun 1975, Sudjoko sudah mempersoalkan perkara yang ia sebut ‘individualisme romantik’ ini. Ia mengutip sepotong puisi karya penyair Belanda, Herman Gorter, untuk menggambarkan kredo yang banyak diyakini para pelukis Indonesia: “Seni adalah ungkapan individual dari emosi individual” (Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie) (Sudjoko 2012: 217). Pengandaian ekspresivis semacam ini cocok dengan pathos eksistensialis yang melanda para intelektual dan seniman Indonesia era 1960/1970-an. Hasilnya adalah cara pandang moralis tentang seni, yakni bahwa seni adalah perkara kejujuran pada diri sendiri dan karenanya menuntut keberjarakan terhadap politik, bahwa politik itu kotor, bahwa seniman yang terlibat dalam politik atau mengangkat persoalan politik adalah seniman yang tidak jujur pada seninya sendiri. Dalam segi itulah pengandaian ekspresivis ini klop dengan estetika formalis yang tadi diuraikan. Di sinilah terwujud sinergi antara ‘keakuan’, ‘komposisi’ dan ‘pembangunan’.
GSRB, Pascamodernisme Avant La Lettre dan Gugatan atas Politik Kebudayaan Orde Baru
Hubungan yang harmonis antara seni lukis awal Orde Baru dan ‘Pembangunanisme’ yang dianut rezim Suharto dengan cepat membiakkan imaji tentang kemapanan. Sehingga pada awal dekade 1970-an, praktis seluruh pelukis menghasilkan lukisan abstrak ataupun dekoratif (berdasarkan olahan atas ragam hias tradisional) yang bisu secara politik. Perbincangan seni rupa—tak pelak lagi dimonopoli oleh isu seputar seni lukis—dipenuhi dengan pembahasan tak habis-habisnya atas pilihan warna, tekstur, bentuk dan aspek-aspek formal-komposisional lainnya. Tak ada ruang untuk membahas kaitan antara seni dan masyarakat, apalagi tentang isu-isu politik. Karena itu, kemapanan ini segera berubah jadi kemandekan. Pada tahun 1970, Indonesia berpartisipasi dalam acara perayaan 25 tahun PBB yang digelar di New York. Untuk itu, sejumlah karya dipilih oleh sekelompok juri yang ditunjuk oleh pemerintah. Pilihan juri ini kemudian menimbulkan keresahan tersendiri sebab banyak karya lama—antara lain lukisan Kusnadi dari tahun 1957—yang dipilih ketimbang karya-karya baru (Sumartono 2001: 23). Ini menunjukkan dekadensi yang timbul akibat kemapanan autistik yang diderita seni rupa Indonesia.
Kejengahan terhadap suasana mapan yang suam-suam kuku itulah yang meledak dalam kontroversi seputar Pameran Besar Seni Lukis Indonesia 1974 yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Praktis seluruh karya yang terpilih sebagai pemenang bersama dalam sayembara itu adalah karya para pelukis senior dengan gaya lukis yang itu-itu juga, yakni lukisan-lukisan A.D. Pirous, Aming Prayitno, Widayat, Irsam dan Abas Alibasyah. Keputusan inilah yang digugat lewat Pernyataan Desember Hitam yang ditanda-tangani oleh empat belas seniman, rata-rata merupakan mahasiswa dari ISI, ITB dan IKJ. Pernyataan ini menyatakan bahwa kerangka pikir yang dianut para juri, mewakili rezim seni rupa yang ada, adalah kerangka pikir yang usang. Selain itu, ditekankan juga pentingnya kemawasan seniman akan dimensi sosial, budaya, politik dan ekonomi, dalam menghasilkan karya seni. Di situ, bisa kita lihat, bagaimana perlawanan atas rezim estetika Orde Baru dinyatakan: menolak kerangka pikir formalistik dengan menanamkan kembali kesenian pada kenyataan sosial-politik.
Perlawanan yang tak diduga-duga ini menimbulkan reaksi yang amat keras di ISI. Seluruh mahasiswa ISI yang terlibat menanda-tangani pernyataan tersebut diskors. Direktur ISI, Abas Alibasyah, pelukis dekoratif yang juga pemenang sayembara kontroversial itu, menyatakan bahwa orientasi sosial-politik dalam manifesto Desember Hitam itu semestinya datang dari mahasiswa jurusan sospol, bukan mahasiswa seni. Kemudian ia mengatakan bahwa aksi-aksi mahasiswa itu bertentangan dengan “pembangunan nasional” dan dapat membahayakan “kesatuan, integritas dan stabilitas nasional” (Sumartono 2001: 24). Tersiar juga kabar bahwa pernyataan Desember Hitam itu mengandung ‘bahaya laten komunis’, sampai-sampai Pangkowilhan (Panglima Komando Wilayah Pertahanan) IV Jawa-Madura, Letjen Widodo mengaku resah dengan perkembangan yang terjadi di ISI. Delapan bulan setelah kontroversi Desember Hitam, dideklarasikanlah Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB) yang antara lain beranggotakan Jim Supangkat, FX Harsono, Muryoto Hartoyo dan didukung oleh paus kritik seni Indonesia, Sanento Yuliman. Di sinilah bermula apa yang Jim Supangkat sebut sebagai ‘seni rupa pemberontakan’ (Supangkat 1993: 13).
Gejolak yang dihasilkan GSRB amat krusial dampaknya bagi perkembangan seni rupa Indonesia. Dalam semangat GSRB, semesta kesenian tak lagi asing dari semesta politik. Seniman tak lagi memposisikan-diri secara moralis di luar konstelasi politik, bak pertapa suci yang jauh dari tetek-bengek kehidupan duniawi dan berfokus hanya pada kontemplasi estetis atas bentuk-bentuk murni dalam pikirannya sendiri. Seniman mulai aktif menginterogasi kenyataan di sekelilingnya. Kegiatan seni jadi tak bisa dipisahkan dari kegiatan politik. Dalam semangat semacam inilah muncul kontroversi di seputar pameran bertajuk “Kepribadian Apa?” di Galeri Senisono, Yogyakarta. Pameran yang melibatkan para seniman muda eksponen Desember Hitam dan GSRB ini menggugat konstruksi ideologis pemerintah Orde Baru tentang ‘identitas nasional’. Pada hari pertama pameran, kapten polisi Wahjoeno segera melarang penyelenggaraan pameran karena mendapati adanya karya pornografis dan pada hari kedua ia menunjuk adanya dua karya yang ‘berbahaya’, yakni Hotel Tower of Asia karya Bonyong Munny Ardhi dan Kartu Remi indonesia karya Slamet Ryadhi (Sumartono 2001: 27). Karya yang pertama merupakan instalasi yang mengangkat isu kesenjangan ekonomi dengan menampilkan pengemis tertidur di emperen hotel berbintang, sementara karya yang kedua menggambarkan karta remi dengan wajah Suharto.
Pada tahun 1979, Jim Supangkat merangkum lima pokok pikiran GSRB. Pada kelimanya kita menjumpai pandangan-dunia baru yang tak mungkin kita temukan dalam tulisan dan karya para pelukis awal Orde Baru. Kelima pokok pikiran itu bisa diringkas seperti ini (Supangkat 2007: 125-126):
- Menolak skema klasifikasi seni rupa ke dalam seni lukis, patung dan grafis, serta menentang pembatasan karya rupa sehingga tidak diciutkan pada salah satu dari wahana seni yang ada.
- Menolak avant-gardisme yang memposisikan seniman sebagai sosok jenius subtil yang “tidak dimengerti masyarakat” serta “percaya pada masalah-masalah sosial yang aktual sebagai masalah yang lebih penting untuk dibicarakan daripada sentimen-sentimen pribadi.”
- Menolak hubungan patronase yang menundukkan seniman muda pada seniman tua (cantrikisme) dan membuka “kemungkinan berkarya” seluas mungkin.
- Menolak pandangan yang mengatakan “seni adalah universal” dengan kembali menginterogasi sejarah seni rupa Indonesia dan mencari konteks historis spesifiknya yang membuatnya tak bisa seutuhnya ditangkap lewat kategori-kategori yang didapat dari teori-teori seni di Barat.
- Memperjuangkan seni rupa yang hidup di tengah masyarakat.
Lima poin ini mengartikulasikan perubahan paradigmatik yang sangat mendasar. Poin pertama tiada lain adalah sebuah pukulan telak bagi iman formalis yang menjadi sokoguru Modernisme seni. Dengan itu, GSRB menolak doktrin ‘kekhasan wahana’ yang sangat puritan seperti dalam estetika Clive Bell, Roger Fry dan Clement Greenberg dan dipraktikkan oleh para pelukis abstrak dan dekoratif kala itu. Poin kedua adalah penolakan atas ekspresivisme yang melanda seniman modern Indonesia pasca-Sudjojono. Dengan itu, GSRB memposisikan diri berlawanan dengan doktrin ‘individualisme romantik’ yang antara lain mengemuka dalam pendirian Oesman Effendi. Dua poin pertama ini saja sudah merepresentasikan suatu balikan cara berpikir seni yang sangat fundamental di Indonesia. Itu masih ditambah lagi dengan penekanan pada eksperimentasi (poin ketiga), pada pembacaan-ulang atas sejarah Indonesia (poin keempat), serta pada ketersituasian seni dalam medan sosial-politik (poin kelima). Dengan kelimanya, GSRB menjadi mimpi buruk bagi rezim estetika Orde Baru.
GSRB membuka cakrawala baru dalam imajinasi artistik seniman Indonesia, khususnya di kalangan muda. Ia menjadi pintu masuk bagi sejumlah kesadaran estetis baru, misalnya kesadaran bahwa seni lukis bukanlah paradigma utama seni rupa dan bahwa seniman bukanlah entitas yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Dua kesadaran penting ini direalisasikan lebih lanjut dalam karya Moelyono pada tahun 1985, Kesenian Unit Desa (KUD). Karya yang merupakan bagian dari proyek advokasi kerakyatan di Tulung Agung ini ditolak oleh para penguji di ISI ketika Moelyono menghadirkan karya tersebut sebagai bagian dari tugas akhirnya sebagai mahasiswa. Alasan penolakan ini mencerminkan masih kuatnya pengandaian estetika formalis di benak para pengajar ISI. Subroto, asisten dekan fakultas seni murni, menyatakan: “Jelas bahwa KUD tidak termasuk lukisan. […] Alasan untuk menolaknya ikut ujian akhir adalah karena ia tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah lukisan. Persyaratan itu antara lain menyebutkan bahwa karya mesti menempati bidang datar dan punya aspek-aspek lukisan tertentu” (Sumartono 2001: 31). Argumen asisten dekan ini jelas merujuk lagi pada doktrin ‘kekhasan wahana’ dan penekanan pada flatness sebagai syarat dan batas seni lukis Modernis dalam kacamata Greenberg. Dengan demikian, nampak bahwa kendati tumbuh kesadaran baru yang radikal di kalangan perupa muda, tetapi birokrat kampus tetaplah berpegang pada kaidah estetika lama. Konflik antara keduanya dan ketiadaan ruang bagi seniman-seniman muda untuk menampilkan karyanya inilah yang mendorong munculnya galeri-galeri alternatif seperti galeri Cemeti (1988).
Kendati GSRB telah berhasil menjebol penjara estetika Modernis dan membangun suatu estetika yang berorientasi sosial, mawas sejarah dan kontekstual, tetapi hegemoni estetika Modernis masih kuat juga. Salah satu sebabnya adalah bahwa estetika tersebut dipegang teguh oleh para pejabat di kampus atas dukungan pemerintah. Sinergi antara para pelukis Modernis dan Orde Baru memang tak dapat dipungkiri. Salah satu syarat wajib penyerahan tugas akhir di ISI pada era 1980-an, misalnya, adalah bahwa karya yang diajukan “mesti berdasarkan Pancasila” (Sumartono 2001: 31). Namun hegemoni estetika ini juga diperkuat oleh fenomena di luar kampus, yakni pasar seni lukis yang memang tengah mengalami ledakan pada era 1980-an. Mula-mula para kolektor dan pembutuh mencari karya-karya old masters seperti Sudjojono, Affandi, Hendra Gunawan dan sebagainya, kemudian beralih ke generasi pelukis yang lebih muda dan akhirnya sampai ke karya-karya abstrak dan dekoratif. Akibatnya, melalui intervensi pasar inilah muncul apa yang disebut Sanento sebagai ‘pemiskinan’ dalam dunia seni lukis Indonesia, yakni pembatasan atas kosa lukis (pengutamaan atas wahana kanvas dan cat minyak daripada kertas dan arang, misalnya) yang mendorong makin miskinnya pengalaman visual kita (Yuliman 2012: 517-518). Jadi mengapa hegemoni estetika Modernis itu tak juga goyah bahkan sampai penghujung dekade 1980-an, antara lain, disebabkan karena pasar seni lukis yang tengah mengalami boom dengan segala pemiskinan pengalaman visual yang dibawanya.
GSRB sering dipersepsi sebagai awal kemunculan estetika pascamodern dalam sejarah seni rupa Indonesia. Nyatanya, identifikasi semacam ini baru muncul pada Biennale Seni Rupa Jakarta IX, tahun 1993. Dalam biennal bertajuk ‘Post-Modernisme’ ini, Jim Supangkat membaptis GSRB sebagai gerakan yang diinspirasikan oleh pascamodernisme. “Seni Rupa Era ’80, yang tampil dalam Bienniale Seni Rupa Jakarta 1993 ini, adalah seni rupa pasca-pemberontakan itu: tidak lagi menentang modernisme, tapi meninggalkannya. Seni rupa ini dikenal pula sebagai seni rupa pasca-modern” (Supangkat 1993: 13). Pembaptisan ini dianggap berlaku surut—mencakup fenomena kesenian yang terjadi sejak dekade 1970-an. Dengan begitu, pembaptisan ini terjadi nyaris 20 tahun setelah gerakannya sendiri berjalan.
Di sini muncul fenomena yang agak janggal. Pertama, GSRB justru bubar saat Lyotard menerbitkan buku yang mempopulerkan pascamodernisme dalam kajian kebudayaan, La condition postmoderne (1979). Artinya, gerakan seni itu berkembang tanpa dibimbing oleh kemawasan teoretis atas pascamodernisme, lebih khusus lagi pascastrukturalisme Prancis. Tentu saja, GSRB dipengaruhi oleh gerakan seni kontemporer di Barat, seperti seni konseptual Fluxus, Dada, seni pop dan sebagainya. Namun beragam praktik seni itu tercipta tanpa bimbingan teori-teori pascastrukturalis atau pascamodernis. Yang terjadi adalah justru sebaliknya: teori-teori pascamodernis dalam banyak hal justru dihasilkan dari pembacaan atas perkembangan seni-budaya di Eropa pasca-Perang Dunia kedua. Jadi menganggap GSRB berpegang pada filosofi posmo berarti merancukan sebab sebagai akibat. Barangkali benar bahwa dalam kerangka pascamodernisme lah para seniman yang bersimpati pada GSRB memperoleh pembenaran teoretis atas praktik mereka selama ini. Namun pembenaran ini sebetulnya tak lebih dari pencocok-cocokan yang tak sepenuhnya pas. Para eksponen GSRB tidak punya urusan dengan Descartes atau Kant; gara-gara dilabeli posmo, mereka sekarang seperti terpaksa harus berurusan dengan Descartes dan Kant (dua sosok yang mungkin baru mereka dengar namanya). Padahal apa yang mereka lawan adalah para dedengkot seni lukis Modernis di tanah air. Dan seni lukis Modernis di Indonesia, seperti telah kita lihat, tidak sama dengan ‘seni lukis Modernis’ dalam definisi baku Modernisme seni Eropa (yang hanya mengakui estetika formalis sebagai dasarnya). Seni lukis Modernis kita juga bercampur dengan paham Romantik seperti ekspresivisme dengan segala spekulasi mistiknya tentang jiwa dan rasa.
Kedua, banyak kecenderungan GSRB dan turunannya yang tidak sama dengan apa yang digambarkan dalam teori-teori pascamodern. Semangat GSRB untuk mengakarkan praktik seni pada praktik sosial-politik, misalnya, justru berlawanan dengan kecenderungan teori-teori pascamodern yang cenderung menempatkan politik dalam bingkai wacana politik. Banyak kritik politik dan aktivitas politik GSRB dan turunannya yang dengan tajam menyasar pada permasalahan ekonomi-politik (instalasi Hotel Tower of Asia karya Bonyong Munny Ardhi dan lukisan-lukisan Dede Eri Supria, misalnya). Radikalisasi atas tendensi politik GSRB juga bisa kita lihat dalam terbentuknya kolektif seni Taring Padi pada 21 Desember 1998. Perlawanan artistik yang menitik-beratkan pada masalah-masalah ekopol ini asing dari tradisi pascamodern yang lebih mengedepankan perkara kultural ketimbang ekonomi-politik; masalah-masalah seputar politik identitas dan politik pengakuan adalah tipikal masalah-masalah yang ditangani teoretisi pascamodernis, bukan masalah kontradiksi ekonomi kapitalis. Tendensi aktivisme GSRB membuatnya lebih dekat dengan, misalnya, pemikiran para perupa avant-garde Soviet pra-realisme sosialis (era 1920-an) ketimbang dengan pemikiran para budayawan pascamodern. Perbedaan ini diperkuat lagi oleh fakta bahwa tak semua pemikir pascamodern memiliki pandangan yang selaras dengan GSRB. Lyotard, sang ‘bapak posmo’ itu sendiri, malah mengedepankan doktrin ‘kekhasan wahana’ dalam bukunya tentang estetika seni rupa, Figure, Discourse. Di sana ia justru menekankan ketaktereduksian visualitas khas seni rupa pada pewacanaan verbal-sastrawi (Lyotard 2011: 7). Karena itu, Lyotard masih bisa bicara tentang keindahan dan kesubliman. Dalam hal itu, estetikanya justru berakar pada Modernisme Greenberg. GSRB jelas lebih gahar ketimbang para pemuja kebagusan kontemporer semacam itu.
Ketiga, tidak semua eksponen GSRB sepakat bahwa gerakan pemberontakan seni itu berlandaskan pada nilai-nilai pascamodern ataupun dapat dijelaskan berdasarkan kerangka teori pascamodern. FX Harsono, misalnya, menyangsikan upaya untuk menafsirkan perkembangan seni rupa Indonesia berdasarkan lensa teoretis dari Barat (Sumartono 2001: 68). Dalam hal ini, kita harus ingat bahwa poin keempat deklarasi GSRB menyebutkan soal pentingnya praktik kesenian yang dilandasi oleh kemawasan atas sejarah seni Indonesia dan kemauan untuk menggali terus-menerus dari sejarah tersebut. Dengan itu, ditekankan konteks khas dari perkembangan seni sejauh setiap praktik kesenian sesungguhnya bersumber dari geliat hidup masyarakat yang konkrit. Jadi penggunaan label dan kerangka berpikir pascamodern, dengan riwayat debatnya sendiri di Eropa, untuk membaca sejarah seni rupa Indonesia, dengan riwayat debatnya sendiri sejak Hindia Belanda, justru bertentangan dengan salah satu prinsip dasar gerakan itu sendiri. Latar historis perjuangan antikolonial yang membidani kelahiran seni rupa modern Indonesia tak bisa diciutkan pada kerangka politik wacana pascakolonial yang merayakan ‘hibriditas’ seperti dikembangkan teoretisi posmo macam Homi Bhabha. Konteksnya lain.
Fakta historis bahwa kemudian GSRB dan berbagai praktik seni rupa alternatif sesudahnya dipersepsi dalam terminologi dan kerangka teori pascamodern punya dampak yang tak sederhana bagi perkembangan estetika seni rupa Indonesia. Salah satu dampak yang paling fatal adalah bahwa patahan terhadap warisan estetika Orde Baru—Modernisme estetik yang bersimbiosis dengan kapitalisme—tidak berhasil diwujudkan secara tuntas.
Warisan Orde Baru bagi Wacana Estetika Hari Ini
Orde Baru berakhir dengan pengunduran-diri Suharto, bukan penggulingan Suharto. Fakta ini sangat krusial bagi perkembangan politik sampai hari ini. Dengan mengundurkan diri, Suharto memotong akselerasi kontradiksi sosial-politik dan ekonomi sebelum memuncak. Pengorganisasian-diri rakyat belum sampai pada tahap konfrontasi terbuka terhadap seluruh warisan Orde Baru. Dengan mengundurkan diri, Suharto membuat kontradiksi yang sedang menajam menjadi pecah ke dalam pertarungan antar elit kelompok kepentingan. Akibatnya, sebagian dari logika kultural Orde Baru masih bisa terselamatkan. Kultur oligarki masih bertahan hingga kini. Cara pandang moralis yang menempatkan gerakan mahasiswa sebagai agen pembaharu, terpisah dari rakyat biasa, masih terus berpengaruh. Struktur ekonomi-politik yang menopang Orde Baru sejak mula belum terjamah sama sekali. Dalam suasana ketaktuntasan konfrontasi atas kebudayaan Orde Baru inilah seni rupa kontemporer Indonesia melangkah hingga hari ini.
Dominasi wacana pascamodernis dalam perbicangan seni rupa era Reformasi juga punya peran dalam memupuk suasana seperti itu. Kita memang tak bisa memungkiri aspirasi emansipatoris yang terkandung dalam berbagai teori pascamodernis. Derrida, misalnya, berbicara tentang pengakhiran atas cara berpikir yang membangun dikotomi dan hierarki serta menekankan pentingnya menyelamatkan yang-lain dari kungkungan penyeragaman. Lyotard menekankan pentingnya merayakan keragaman narasi lokal yang partikular dan mewanti-wanti setiap upaya yang hendak menundukkan keragaman itu pada suatu narasi besar yang berpretensi merangkum semuanya. Namun kerapkali kerangka berpikir semacam itu diketengahkan dalam rumusan yang amat abstrak dan jauh dari kenyataan, jauh dari kekonkritan sejarah. Kita mesti membela ‘yang-lain’—tentu saja. Tetapi bagaimana bila ‘yang-lain’ itu Hitler? Kita mesti menghargai wawasan lokal yang partikular—tentu saja. Tetapi bagaimana bila tradisi di suatu tempat mengharuskan seorang perempuan untuk ikut bakar-diri ketika suaminya mati, atau kepatuhan penganut kepercayaan minoritas pada penganut kepercayaan mayoritas sudah menjadi tradisi dan kebudayaan setempat? Dalam kasus-kasus seperti itu, logika kulturalis pascamodern tak bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Meera Nanda sudah menunjukkan bagaimana cara berpikir semacam itu membuahkan justifikasi, atas nama tradisi, bagi masyarakat yang berkasta dan terstruktur oleh hierarki gender di India. Tradisionalisme semacam ini adalah masalah klasik yang diakibatkan oleh pascamodernisme.
Lebih jauh lagi, dengan mengecam cara berpikir keilmuan sebagai “warisan Pencerahan yang mengantarkan kita ke Auswitczh”, pascamodernisme sebenarnya bisa dilihat sebagai kelanjutan dari semangat zaman Romantik. Akibat dari pencampakan cara berpikir rasionalis dan ilmiah itu adalah munculnya gelagat kultural untuk kembali ke intuisi, ihwal rasa-merasa dan kepekaan batin. Dalam varian pascamodernisme yang dekat dengan New Age dan mistisisme, gelagat semacam itu mencolok sekali. Dampaknya bagi diskusi estetika adalah kembalinya gambaran tentang seniman sebagai sosok perenung yang menciptakan karya dari permenungan, pergulatan batin dan eksplorasi tubuhnya sendiri. Ke-adiluhung-an seniman dan proses kreatif kembali dimistikkan seperti halnya para pelukis Modernis di awal masa Orde Baru. Walaupun karyanya boleh jadi terkesan kontemporer, dalam rupa instalasi misalnya, tetapi suasana batinnya mirip dengan suasana batin para pelukis abstrak era 1960-an. Dalam obsesi pada yang serba-sublim dan serba-subtil ini, dimensi sosial dari praktik artistik cenderung surut ke belakang. Kalaupun dimensi sosial ini muncul, itupun seringkali terjadi lewat pencomotan dangkal atas idiom-idiom teori pascamodernis—mungkin juga dilakukan ‘atas instruksi bapak kurator’—semata demi terkesan up-to-date dan mendalam. Usaha-usaha untuk mengakarkan praktik seni pada lingkup kehidupan sosial yang menjadi motor GSRB seperti terasa usang bagi para seniman jenis ini.
Suasana batin semacam itu menunjukkan kuatnya konsepsi tentang seniman sebagai creator alih-alih sebagai organizer. Dalam kesadaran yang telah dibukakan GSRB bahwa seniman tak berbeda jenis dari rakyat biasa dan implikasinya bahwa setiap orang adalah seniman, maka peran seniman profesional semakin didorong untuk menjadi sosok yang mengorganisasikan masyarakat ketimbang menjadi pemasok nilai-nilai estetis yang sublim dan berjarak dari mereka. Karena setiap orang adalah seniman, maka setiap kenyataan sosial adalah karya seni. Implikasinya produk yang dihasilkan sang seniman profesional, bekerjasama dengan masyarakat, semestinya adalah kenyataan sosial yang baru, bukan sekadar ‘benda seni’. Kesadaran tentang seniman sebagai organizer ketimbang creator semacam itu hidup dalam beberapa kolektif seni di tanah air (inisiatif seni di Jatiwangi, berbagai gerakan street art dan seni video partisipatoris, misalnya). Namun mayoritas seniman Indonesia saat ini, khususnya yang berpameran di galeri komersial dan menjual karyanya secara konvensional, sepertinya masih berada dalam batas-batas prakonsepsi seniman sebagai perenung yang menciptakan karya berisi renungan moral tertentu sebagai ‘catatan kritis’ terhadap hiruk-pikuk kenyataan.
Boom seni rupa era 2000-an turut memberi warna pada wacana estetika warisan Orde Baru. Selama 2000-2010, tak kurang dari 37 galeri komersial baru bermunculan di kota-kota besar (Hujatnikajenong 2015: 194). Peran kolektor dan galeri dalam mengarahkan, via kurator, jenis karya yang mesti dihasilkan seniman sangat besar. Dalam laporannya tentang sebuah pameran lukisan di Magelang tahun 2001, Aminudin Siregar mencatat betapa praktik artistik seniman Indonesia kontemporer semakin diarahkan oleh para kolektor.[9] Di tangan para kolektor, karya seni tak ubahnya seperti tanah, yakni komoditas yang punya nilai investasi tinggi apabila dirawat dan ‘digoreng’ dengan tepat. Dalam suasana seperti ini, hanya karya seni yang mewujud dalam benda seni saja lah yang akan menjadi sorotan dunia seni—sebab hanya karya semacam itulah yang bisa dijual. Sementara karya seni yang mewujud dalam hubungan sosial dan kenyataan sosial yang baru—jenis karya dan praktik seni yang sebetulnya berakar pada pemberontakan seni GSRB—tak punya peran dalam medan seni rupa Indonesia yang telah terintegrasi dengan pasar itu. Dengan demikian, dalam dunia seni rupa kontemporer mainstream di Indonesia ada semacam pembalikan ke sejenis formalisme baru yang berakar pada estetika formalis Orde Baru, yakni sejenis estetika yang menciutkan karya seni pada aspek kebendaannya dan berbicara tentang keindahan dan kesubliman dalam batas-batas benda seni itu sendiri. Semua itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum selesai membuat perhitungan dengan Orde Baru.***
Kepustakaan:
Bell, Clive. 1914. Art. New York: Frederick A. Stokes Company.
Bujono, Bambang. 2004. “Sejumlah koleksi, sepotong sejarah dan perubahan”. Dalam Enin Supriyanto & JB Kristanto, ed. Perjalanan Seni Lukis Indonesia: Koleksi Bentara Budaya. Jakarta: KPG, 67-130.
Cockcroft, Eva. 1985. “Abstract Expressionism, weapon of the Cold War”. Dalam Francis Frascina, ed. Pollock and After: The Critical Debate. New York: Harper and Row, 125-133.
Collingwood, R.G. 1938. The Principles of Art. Oxford: Clarendon Press.
George, Kenneth M. 2005. Politik Kebudayaan di Dunia Seni Rupa Kontemporer: A.D. Pirous dan Medan Seni Indonesia, diterjemahkan oleh Fadjar I. Thufail dan Atka Savitri. Yogyakarta: Cemeti Art Foundation dan Retorik Press.
Effendi, Oesman. 2007. “Seni lukis di Indonesia: dulu dan sekarang”. Dalam Ugeng T. Moetidjo dan Hafiz, ed. “Seni Lukis Indonesia Tidak Ada”. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 8-19.
Greenberg, Clement. 1999a. “Modernist Painting”. Dalam Charles Harrison dan Paul Wood, ed. Art in Theory: 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas. Oxford: Blackwell, 754-760.
——– . 1999b. “Towards a Newer Laocoon”. Dalam Charles Harrison dan Paul Wood, ed. Art in Theory: 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas. Oxford: Blackwell, 554-560.
Hujatnikajennong, Agung. 2015. Kurasi dan Kuasa: Kekuratoran dalam Medan Seni Rupa Kontemporer di Indonesia. Jakarta: Marjin Kiri.
Iskandar, Popo. 2012. “Seni melalui virtuositas: suatu potret tentang Ahmad Sadali”. Dalam Bambang Bujono dan Wicaksono Adi, ed. Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 201-206.
Lyotard, Jean-François. 2011. Figure, Discourse, trans. Antony Hudek dan Mary Lydon. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Saunders, Frances Stonor. 1999. The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters. New York: New Press.
Siregar, Aminudin TH. 2010. Sang Ahli Gambar: Sketsa, Gambar dan Pemikiran S. Sudjojono. Tangerang dan Jakarta: S. Sudjojono Center dan Galeri Canna.
——– . 2012. “Seni rupa Yogyakarta: gemuruh pasar yang tidak mencerdaskan”. Dalam Bambang Bujono dan Wicaksono Adi, ed. Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 545-548.
Sudjojono, S. 1946. Seni Loekis, Kesenian dan Seniman. Yogyakarta: Indonesia Sekarang.
——– . 1985. “Seni Rupa yang Menjawab Tantangan Masa Kini”. Dalam majalah SANI, 28 Juni 1985, 35-38.
——– . 2007. “Menuju ke Corak Seni Lukis Persatuan Indonesia Baru”. Dalam Ugeng T. Moetidjo dan Hafiz, ed. “Seni Lukis Indonesia Tidak Ada”. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 28-31.
Sudjoko. 2012. “Kita Juga Punya ‘Romantic Agony’”. Dalam Bambang Bujono dan Wicaksono Adi, ed. Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 211-220.
Sumartono. 2001. “The role of power in contemporary Yogyakarta art”. Dalam Outlet: Yogyakarta within the Contemporary Indonesian Art Scene. Yogyakarta: Cemeti Art Foundation, 17-62.
Supangkat, Jim. 1993. “Seni rupa era ‘80”. Dalam Katalog Bienniale Seni Rupa Jakarta IX 1993, 13-27.
——– . 2007. “Lima jurus gebrakan Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia”. Dalam Ugeng T. Moetidjo dan Hafiz, ed. “Seni Lukis Indonesia Tidak Ada”. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 123-124.
Thamrin, Misbach. 2004. “Pameran nasional grafik Lembaga Seni Rupa Indonesia Lekra”. Dalam Bambang Bujono dan Wicaksono Adi, ed. Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 151-153.
Yuliman, Sanento. 1976. Seni Lukis Indonesia Baru: Sebuah Pengantar. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta.
——– . 2012. “Mendung pengiring boom”. Dalam Bambang Bujono dan Wicaksono Adi, ed. Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 517-521.
————–
[1] Artikel ini pernah dipresentasikan sebagai makalah diskusi dalam simposium OK. Video bertajuk Cara Orde Baru Menciptaken Manusia Indonesianya (2015).
[2] “Kebagusan dan kebenaran ialah satu. Kebenaran bagaimana juga tentu bagus, asal saja keluarnya kebenaran tadi tak berdusta pada hati sendiri. Dari itu tak heran kita mengapa anak kecil yang lari-lari telanjang di tengah jalan, kelihatan segala-galanya, toh tetap bagus. Dan muka mereka meskipun penuh ingus toh simpatik. Sebab apa? Sebab barès [terus terang], sebab tak berlagak, sebab benar dan dengan sendirinya bagus. Tetapi bagus yang hendak bagus saja yang tidak mengandung kebenaran di dalamnya, biasanya malah tidak bagus. Kalau pembaca tidak percaya, cobalah anak tuan yang baru berumur 6 bulan, tuan pangkas, tuang potong polka, lalu tangannya tuan tolak-pinggangkan, dan tuan tengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sebagai mandor besar kebun mengontrol pekerjaan kuli-kulinya, tuan terkejut akan efeknya. Tuan ketawa melihat anak tadi. Sebab ‘kebagusan’ tadi tidak mengandung kebenaran. Jadi kebenaran zonder [tanpa] bermaksud mencari ‘bagus’ saja tetapi mencari kebenaran sebagai kebenaran, tentu tetap bagus. Kebagusan zonder kebenaran sebaliknya: jelek, njeléhi [menyebalkan], mentertawakan [menggelikan].” (Sudjojono 1946: 40)
[3] “Kalau Barat, yang sudah menguasai materi, lalu kemudian jadi bosen dan muak pada materi lalu terus pergi ke abstrak, dll, itu saya mengerti. Tetapi kok di Indonesia yang baru saja keluar dari kekerasan 350 tahun cawe-cawe [ikut serta] juga ke abstrak, ini kira-kira sebab apa? Kapan kita gablek [mempunyai] materi, kok sudah jadi bosan materi? Malah kalau yang rakus materi saya lebih sering lihat dan baca. Jadi dalam praktek, yang muak materi saya betul-betul nggak pernah lihat, tapi di seni lukis le muak materi koq koyo ya-ya-o [rasa muaknya atas materi kok seolah sudah yang paling tak tertahankan]. Jadi kalau ada teori bahwa seni adalah gambar dari zamannya, maka satu-satunya kesimpulan adalah bahwa seni lukis sekarang di Indonesia adalah pemantulan dari kehidupan yang munafik; sok suci, tapi sebenarnya butuh daging bauk, kalau gelap mek-mek brutu. Kadang-kadang malah saya dengar pelukis ini omong besar: ‘saya modern, saya kontemporer. Kalau kamu tidak mengerti, kamu sudah tidak punya nomor lagi. Kamu kolot, kamu ketinggalan zaman. Kamu hanya mengerti yang kasat mata saja. Hanya orang-orang tertentu mengerti saya.’ Ini kok macam ilmu klenik! Makin tidak dimengerti, makin bangga, dan merasa tinggi sekali kedudukan kastanya!” (Sudjojono 1985: 37-38)
[4] “That visual art should confine itself exclusively to what is given in visual experience, and make no reference to anything given in other orders of experience, is a notion whose only justification lies, notionally, in scientific consistency. Scientific method alone asks that a situation be resolved in exactly the same kind of terms as that in which it is presented – a problem in physiology is solved in terms of physiology, not in those of psychology; to be solved in terms of psychology, it has to be presented in, or translated into, these terms first. Analogously, Modernist painting asks that a literary theme be translated into strictly optical, two-dimensional terms before becoming the subject of pictorial art – which means its being translated in such a way that it entirely loses its literary character.” (Greenberg 1999a: 758)
[5] “A. Manap, tampil dengan surprise melalui cukilan kayunya Aksi Tani. Tema dan pengungkapannya adalah sederhana sehingga massa secara sepintas lalu akan mudah memperoleh kesan. Hal yang menarik di samping itu, dalam ruang-tangkap (scope) dari bidang cukilannya yang terisi penuh di mana ia cukup menciptakan suasana yang megah dari suatu barisan raksasa kaum tani.” (Thamrin 2004: 153)
[6] Bandingkan juga pengamatan Frances Stonor Saunders atas strategi kebudayaan Amerika Serikat dalam ‘membungkus’ para maestro Modernis lain sehingga terlihat menguatkan posisi AS dalam Perang Dingin: “The art and sculpture exhibition was curated by James Johnson Sweeney, art critic and former director of New York’s Museum of Modern Art, which was contracted to organize the show: Works by Matisse, Derain, Cezanne, Seurat, Chagall, Kandinsky and other masters of early twentieth century modernism were culled from American collections and shipped to Europe on 18 April, aboard the appropriately named SS Liberté. Sweeney’s press release made no bones about the propaganda value of the show: as the works were created ‘in many lands under free world conditions’, they would speak for themselves ‘of the desirability for contemporary artists of living and workinginan atmosphere of freedom’” (Saunders 1999: 119).
[7] “Dalam percakapan kami, sang pelukis tetap menekankan bahwa setia orang bebas untuk melihat ada gambarmanusia atau pemandangan alam dalam Mentari Setelah September 1965. Hal itu tak jadi masalah. Hal yang mengganggunya adalah penafsiran yang tak tepat mengenai posisi politik karya tersebut. […] Seperti yang ia katakan, dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia: ‘It is too much’.” (George 2005: 42)
[8] “Jadi sebelum gambar burung itu jadi, hal itu harus pergu dahulu dengan sendirinya ke jiwa kita. Sebab jiwa itu mempunyai watak yang lain-lain, umpamanya; rasa hidup filsafat, perasaan warna, perasaan indah itu lain-lain dan sebagainya. Karena nationaliteit mereka, maka buah proses yang ada pun akan lain pula. Dan di sinilah terjadi corak dan stijl gambar itu.” (Sudjojono 2007: 29)
[9] “Ini berupa peristiwa nyata, yakni lemahnya posisi tawar seniman, terjadi dalam sebuah pameran Not Just Political pada 10-17 November 2001 di Museum Widayat, Mungkid, Magelang. […] Pameran itu menggelar pula aksi melukis seniman yang berpameran. Panitia menyiapkan potongan kanvas, cat minyak, atau akrilik. Melalui mikrofon Oei Hong Djien dan Widayat memanggil-manggil nama seniman untuk tampil dan menunjukkan kebolehanna melukis. Maka pelukis Entang Wiharso, Yuswantoro Adi, Alfi, Nurkholis, Made Sukadana, Made Palguna, Nasirun, dan beberapa nama lain, langsung duduk di depan kanvas dan mulai menyabetkan kuas. Setelah lukisan selesai, paniia berharap Widayat member semacam penilaian, misalnya: apik! bagus! nilainya 8! Adapun Oei Hong Djin di mikrofon seenaknya menanyakan harga jual.” (Siregar 2012: 547)